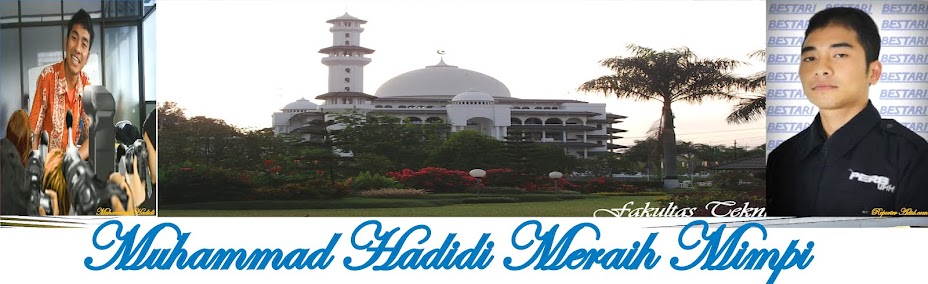Oleh
Muhammad Hadidi
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
Makna simbol-simbol agama yang
digunakan dalam masyarakat, tak selalu seluhur yang mereka klaim dan dakwakan.
Permainan simbol, tak jarang menyihir, menjebak, menipu, sekaligus memerangkap
orang yang terkesima. Ilmu tentang penafsiran simbol-simbol, semiotika, selalu
perlu untuk mengungkap makna di balik simbol-simbol tersebut. Berikut
perbincangan Burhanuddin dari Jaringan Islam Liberal (JIL) Kamis lalu (8/12)
dengan Radhar Panca Dahana, penyair yang kini mengajar sosiologi kebudayaan di
Universitas Indonesia.
Makna simbol-simbol agama yang digunakan
dalam masyarakat, tak selalu seluhur yang mereka klaim dan dakwakan. Permainan
simbol, tak jarang menyihir, menjebak, menipu, sekaligus memerangkap orang yang
terkesima. Ilmu tentang penafsiran simbol-simbol, semiotika, selalu perlu untuk
mengungkap makna di balik simbol-simbol tersebut. Berikut perbincangan
Burhanuddin dari Jaringan Islam Liberal (JIL) Kamis lalu (8/12) dengan Radhar
Panca Dahana, penyair yang kini mengajar sosiologi kebudayaan di Universitas Indonesia.
BURHANUDDIN (JIL): Mas Radhar, apa makna
agama dalam hidup Anda?
|
|
RADHAR
PANCA DAHANA: Agama buat saya adalah bentuk aturan-aturan yang diberikan pada
saya sejak kecil. Aturan itu menetapkan batas-batas kapan atau di mana saya
harus berhenti melakukan sesuatu. Mungkin ada reward atau pahala bagi yang menaati arutan itu. Tapi, kalaupun ada,
apa reward-nya? Kalau aturan yang
datang dari guru, orangtua, pemerintah, atau institusi perusahaan, biasanya ada
batasan punishment dan reward-nya yang jelas. Kalau kita
melewati batas itu, sanksi atau punishment-nya
jelas.
Namun
dalam agama, punishment itu mungkin
berasal dari masyarakat. Kalau saya salat atau ngaji dengan sembarangan, saya
akan dimaki-maki orang. Tapi kalau saya melakukan hal luar biasa, reward-nya mungkin tak akan langsung
didapat. Itulah pengertian saya tentang agama sebagai kenyataan sosial. Secara
individual, pengertiannya tentu lain lagi. Sebab, pemahaman keagamaan itu harus
ditelusuri pelan-pelan berdasarkan pengalaman pribadi-pribadi, tidak hanya dari
ajaran-ajaran.
JIL: Agama dalam pengertian itu
tampaknya terlampau mentitikberatkan soal reward
dan punishment?
Ya.
Memang, ketika agama diformalisasi menjadi pemahaman yang lebih sosiologis dan
kultural, dia mau tidak mau harus berkompromi dengan pemahaman-pemahaman atau
aturan main yang ada di masyarakat, seperti ketentuan-ketentuan adat, norma,
dan hukum formal yang berlaku. Karena itu, agama yang berada di sekeliling kita
adalah juga salah satu dari semua sistem itu.
Artinya,
mau tidak mau, agama itu sendiri juga harus berkompromi dengan unsur lain dalam
masyarakat, supaya tidak terjadi benturan-benturan. Kalau sudah berbenturan,
akibatnya adalah kebingungan umat. Dan kalau umat bingung, akan ada sebagian
orang yang akan menolak agama. Jadi, agama sendiri harus menyesuaikan diri,
apalagi manusianya.
JIL: Bagaimana agama diajarkan pada Anda
selama ini?
Melalui
cara-cara yang umum di masyarakat kita. Mediumnya adalah dongeng-dongeng,
pantangan-pantangan, dan perintah-perintah yang keras. Misalnya, kamu harus
puasa, harus ini dan itu. Itu
mungkin bagian dari cara dan proses internalisasi nilai-nilai agama agar pada
masa berikutnya kita punya pergaulan yang kuat dengan agama.
Tapi
yang perlu digarisbawahi, cara seperti itu belum tentu melahirkan orang-orang
baik. Mencetak orang baik itu juga ditentukan lagi oleh kualitas tiap-tiap
orang dalam menghayati dan mengapresiasi hidupnya. Orang yang memang
disosialisasi atau diinternalisasikan dengan kaidah agama yang kencang, belum
tentu akan menjadi orang yang baik. Sebaliknya, orang yang tak begitu kental
dengan cara sosialisasi seperti itu, belum tentu juga akan otomatis jahat.
JIL: Apa komentar Anda soal paham agama
keras yang belakangan tampak sudah mulai mengancam kehidupan seni?
Agama
mestinya tidak sekerdil itu. Agama terlalu lapang dan luas kalau cuma diwakili
oleh orang-orang berpaham sejenis itu. Politik dan pemerintahan juga terlampau
luas untuk sekadar diwakili satu-dua polisi
yang melarang seniman untuk membaca puisi. Jadi, kelompok-kelompok seperti itu
tak bisa mewakili paham keagamaan yang lapang.
Dalam
kehidupan pribadi, saya pasti punya pemahaman agama sendiri. Karena dibentuk
kenyataan hidup, saya termasuk orang yang cenderung mempertanyakan semua dogma,
aksioma, dan ketentuan-ketentuan yang digambarkan masyarakat sebagai sesuatu
yang sudah ditabukan. Saya kira, pemahaman-pemahaman klasik atau tradisional
tentang agama sudah mencapai tingkat kebekuan tertentu yang membuat banyak
orang terpenjara.
JIL: Dogma-dogma agama sekalipun
sebetulnya absah saja dipertanyakan?
O,
ya. Kita punya akal, kok! Mempertanyakan dogma-dogma itu tidak ada kaitannya
dengan mempertanyakan Tuhan sendiri. Sebab, dogma-dogma itu belum tentu Tuhan
yang bikin. Kebanyakan dogma justru dibikin oleh kita-kita sendiri, dan ia
terkadang sudah bercampur-baur dengan dogma dari agama lain, tradisi, kebiasaan,
hukum adat, hukum formal, hukum kolonial, dan macam-macam. Sebuah dogma tak
jarang campuran dari itu semua. Di situ misalnya, juga bisa bermain
kepentingan-kepentingan kaum feodal.
JIL: Banyak yang takut mempartanyakan
dogma-dogma yang difatwakan para pemuka agama. Kesannya melawan kehendak Tuhan,
gitu…
Hidup
kita ini, sekujur tubuh ini, selalu dipenuhi dogma-dogma. Dogma itu
bermacam-macam, tidak terbatas pada dogma agama. Ada dogma ideologi, politik, tradisi, dll.
Kita harus melihat secara jujur bahwa dogma-dogma itu adalah bentukan atau
sebuah konstuksi sosial. Dalam proses bentukan masyarakat itu, bergabunglah
beberapa kekuatan, beberapa unsur. Jadi, kalau bicara dogma agama, biasanya
tidak akan murni bicara soal agama saja, tapi juga ikut serta pikiran-pikiran
orang di dalamnya.
Ada banyak kepentingan yang juga bermain, baik ekonomi,
politik, maupun budaya. Itu yang harus kita periksa betul. Kalau memang dogma
itu pada akhirnya sudah tak sesuai dengan kenyataan saat ini, dan justru
membatasi potensi kemanusiaan kita, saya kira dogma itu sudah tak ilahiah lagi.
Kalau masih ilahiah, dia pasti akan memberi ruang sebesar dan seluas mungkin
bagi tiap manusia untuk mengoptimalkan peran yang sudah difitrahkan kepadanya.
Berkah itu misalnya dapat berupa telinga, hidung, otak, dll. Itu semua perlu
kita optimalkan ke tingkat yang paling tinggi, dan kalau bisa sampai menuju
Tuhan itu sendiri.
JIL: Dogma dan tafsir atas agama itu
tentu tidak tunggal. Sebagai makhluk yang diberi berkah macam-macam tadi,
bagaimana cara menyikapi berbagai dogma itu?
Saya
tak berani memberi saran, karena ini soal yang sangat subyektif, personal, dan
tidak saya anjurkan bagi orang lain. Latar belakang saya tentu berbeda dengan
orang lain. Saya punya latar belakang budaya, akademis, dan kehidupan sendiri
yang berbeda. Karena itu, cara tiap-tiap kita dalam menghadapi hidup juga akan
sangat berbeda-beda.
Sebagai
sikap pribadi, bukan sebagai saran, saya menghadapi itu semua dengan
mengandalkan integritas, dan independensi diri. Saya harus merdeka dalam
menghadapi semua itu, seraya berusaha menggali pemahaman yang akan saya yakini
dengan hati nurani saya sendiri. Jadi tidak perlu bergantung pada apapun.
Dalam
menghadapi dogma-dogma itu, saya juga tidak ingin terjebak konflik kepentingan
atau vested interest, apalagi
terjebak ideologi tertentu. Maju atau mundur, hidup atau mati, itu saya lakukan
karena pilihan sendiri, bukan karena orang lain menganjurkan. Kalau pun ada
satu hal di luar diri yang harus saya kaitkan dengan diri saya, itu cuma satu
saja: Tuhan itu sendiri.
JIL: Apakah perkembangan agama ke depan
akan menuju slogan “Tuhan, yes! agama, no!�
Harus
kita akui, kecenderungan dunianya, pahit-manisnya, asam-regesnya, memang sedang
seperti itu. Benar, semua orang memang tetap merindukan Tuhan. Tapi, ketika
memasuki Tuhan melalui suatu modus atau mekanisme yang disebut agama, banyak
orang yang berkeberatan dan mulai memilah-milah mana yang lebih enak. Buddha,
Yahudi, Islam, atau apa? Di Eropa, banyak sekali orang yang memilah-milah
seperti itu. Banyak orang yang cenderung memilih Buddha karena dianggap lebih
longgar, lebih cocok dengan psikologi mereka sebagai orang modern, serta
alasan-alasan lain.
Kalau
masuk Islam, konon mereka merasa repot. Orang yang benar-benar berhasrat mencari
Tuhan sebagai bentuk pengabdian dari keseluruhan entitas dirinya, mungkin
memilih Islam. Tapi untuk rata-rata, saya kira orang akan lebih memilih Buddha.
Contoh yang memilih Buddha di Barat adalah penyanyi kita, Anggun C. Sasmi.
Madonna justru memilih mistik Yahudi, Kaballa.
Jadi,
agama dalam pengertian yang saya jabarkan tadi, memang lama-lama akan ditolak.
Terlebih kalau agamanya dijabarkan, dikelola, didefinisikan, dan diformulasikan
dengan cara-cara yang sangat kaku. Agama itu sejatinya tidak kaku, tapi
pengelolaan, pendefinisian, dan formalisasinya yang sebenarnya menjadikan agama
itu sangat kaku.
JIL: Bagaimana tafsiran anda atas
beberapa organisasi sosial keagamaan yang memaksakan tafsir keagamaan mereka
dengan kekerasan pada orang lain?
Persoalan
ini sebenarnya sudah lewat dari soal agama. Persoalan religius dan spiritual,
kadang melampaui soal-soal sosial dan politik. Bagi saya, gejala itu hanya soal
cara sebuah organisasi membangun bargaining
power atau bargaining position organisasinya. Pada akhirnya kita tahu,
ujung-ujungnya juga bermuara pada perolehan akses-akses politik, ekonomi,
ataupun hukum.
Itu
permainan biasa dari kelompok-kelompok sosial-politik yang sedang
berkontestasi. Bahwa mereka menggunakan simbol-simbol agama, itu tak lain
dengan modus atau tujuan reifikasi atau pembendaan simbol-simbol itu tadi.
Jadi, agama yang dihadirkan sesungguhnya bukan lagi agama an sich, agama yang ilahi, tapi agama yang sudah pekat kepentingan
sosiologis.
Yang
dimaksud dengan agama sosiologis adalah agama sebagaimana yang dipahami oleh
komunitas mereka saja. Itu yang pertama. Yang kedua, gejala ini juga dipicu
tarikan-tarikan kehidupan pragmatis dan materialistis. Orang-orang yang pada
mulanya memiliki kemampuan mendalami agama, berjiwa pengabdi, berdisiplin, dan
punya ketekunan hidup dalam kesahajaan (asketis), sayangnya juga tertarik ke
dalam sentrum yang pragmatis itu.
Akhirnya,
mereka mengurusi kepentingan-kepentingan yang terlalu sekuler, seperti masuk
parpol, membikin perusahaan, dan tak lupa ikut korupsi sana-sini. Mereka
kemudian kehilangan daya resap, apresiasi, dan etos untuk pendalaman agama itu
sendiri.
Gejala
seperti itu bisa saja terjadi pada lembaga-lembaga agama yang sudah mapan
seperti NU dan Muhammadiyah. Keduanya sangat mungkin menjadi balon-balon yang
tertarik angin ke kiri-kanan. Sementara dulu mereka begitu kuat berakar pada
masyarakat, sekarang bisa saja mereka akan menjadi balon gas yang tertarik ke
mana-mana. Tarik-tarikan itu disimbolisasikan oleh pesona kematerian.
Jadi,
sekarang kita sedang mengalami materialisasi yang sangat luar biasa. Itu tidak
hanya dialami agama, tapi juga lini-lini kebudayaan kita secara luas. Makanya,
saat ini membuat karya seni juga agak susah, karena harus berhadapan dengan
kenyataan. Kalau tidak mampu berkompromi dengan kenyataan, seseorang akan
berhenti berkesenian. Orang yang menolak pembendaan akan mampus sendirian.
JIL: Bagaimana memahami simbol-simbol
agama agar kita tidak tertipu oleh permainan di baliknya?
Kita
perlu masuk ke pemahaman apa makna simbol itu sesungguhnya. Kalau masyarakat
tak paham, khususnya tentang proses reifikasi simbol atau penggunaan simbol itu
untuk mendapatkan sesuatu, mereka akan manut
dengan klaim kelompok pemakai simbol. Mereka akan mengamini kalau simbol itu
juga mewakili dirinya. Padahal, simbol itu sudah tidak lagi mewakili dirinya.
Itu cuma mewakili kepentingan atau tafsiran individu atau kelompok terbatas
pengguna simbol itu saja.
Tapi
memang sayang, masyarakat di negeri yang paternalistik ini belum juga sampai
pada pemahaman seperti itu. Di negeri lain, orang-orang sudah tidak akan
gampang lagi tertipu oleh simbol-simbol. Begitu mau masuk suatu agama atau
kelompok tertentu, misalnya, mereka lebih dulu akan menyelidiki seluruh
aspeknya dengan baik. Misalnya, seorang Prancis yang mau masuk Islam, dia akan
sudah tahu segala aspek yang perlu diketahui tentang Islam. Jadi, begitu dia
masuk, dia sudah bisa membedakan ciri Islam Timur Tengah dengan Islam Asia
Tenggara. Kita kan tidak seperti itu, malah sebaliknya,
menerima saja sesuatu secara taken for
granted. Jadi, simbol-simbol itu pun dimakan seperti memakan roti lapis
legit.
JIL: Mas Radhar, para pelaku bom bunuh
diri itu pandai sekali menggunakan simbol-simbol agama untuk menangguk simpati
umat Islam agar mengamini luhurnya perjuangan mereka. Komentar Anda?
Saya
selalu mengajak orang untuk tidak memikirkan kaitan antara terorisme dengan
agama. Tindakan mereka itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Kita
semua tahu, itu semua adalah buah dari indoktrinasi, ideologisasi, permainan
uang, dan tekanan terhadap orang-orang yang sudah frustasi. Mereka digaet untuk
membayar dosa-dosanya, dan surat
pengampunan dosanya adalah bunuh diri. Dengan bom, mereka merasa dosanya akan
hilang dan masuk surga.
Terorisme
selalu tak ada hubungan dengan agama. Itu hanya soal organized crime atau bagian dari aksi kriminal yang terorganisasi,
seperti kelompok mafia. Jadi, tak ada urusannya dengan agama. Kalau tiba-tiba
setiap mafia menggunakan salib di leher, apakah dia bisa dibilang
mafia-Kristen?
Karena
itu, saya menganjurkan Mendiknas untuk berinisiatif mengajarkan mata pelajaran
semiotika (ilmu tentang simbol-simbol) di sekolah-sekolah. Dengan kemampuan
semiotika, seseorang akan mampu membaca simbol tidak secara kasat mata. Dia
akan membaca sesuatu di balik simbol.
Misalnya,
kalau membaca koran, jangan dibaca harfiah saja. Karena selalu ada something atau sesuatu di balik berita,
dan itu perlu diungkap. Ketika setiap orang melompat ke balik simbol, ia akan
menemukan dunia antah-berantah dan mampu menentukan tafsirnya sendiri-sendiri
atas kenyataan. Jadi, mereka mampu memungut signifikansinya sendiri-sendiri,
dan semua tidak akan tertipu. Dengan begitu, akan banyak pilihan cara pandang.
JIL: Apa pentingnya semiotika dalam membaca
simbol-simbol agama?
Kalau
mencermati khazanah budaya yang bernama agama, orang tidak semestinya langsung
mengatakan “memang benar, begitu!â€, tapi harus mengecek dan meneliti ulang.
Kelebihan manusia itu ada pada kecerdasannya. Kecerdasan itulah yang harus dia
pergunakan dalam menghadapi setiap gejala, setiap gerak kehidupan. Kalau sudah
berhenti bertanya, menerima begitu saja apa yang ada, maka manusia sama saja
dengan binatang. Dan ingat, proses demokratisasi dan pencerahan yang
sesungguhnya, akan berlangsung ketika setiap kepala yang berbeda-beda itu
diperbenturkan dalam bentuk perdebatan. Itulah yang akan melahirkan ide-ide.
JIL: Apa komentar anda soal meningginya
tingkat intoleransi di negeri ini?
Perlu
disadari, negeri ini dibangun oleh konstelasi berbagai kekuatan yang
masing-masing sudah eksis lebih dulu. Dulu, ada kerajaan-kerajaan kecil yang
sudah berdiri sejak lama, jauh sebelum Indonesia terbentuk. Nusantara ini
juga dibangun oleh proses persilangan kebudayaan yang luar biasa. Artinya,
tidak ada satu suku dan agama pun di negeri ini yang berhak mengatakan dirinya
yang paling utuh dan berhak, karena semuanya hasil persentuhan dengan
budaya-budaya di sekelilingnya maupun dari luar. Semuanya hibrid.
Jadi,
tidak ada orang atau kelompok yang betul-betul otentik menjadi pemilik bangsa
ini. Karena itu, kita harus terbiasa dengan tingkat pergaulan yang majemuk.
Tapi mengapa kebiasaan itu tiba-tiba hilang atau berubah menjadi kebringasan?
Saya kira, ada hal-hal yang luar biasa hebat yang telah penetrasi memasuki
sumsum masyarakat yang majemuk ini. Dan, itu mampu mengubah banyak hal.
Apakah modal sosial-budaya bangsa ini
mampu mengukuhkan kembali sendi-sendi toleransi?
Ya,
saya optimis, dengan pengandaian bahwa setiap manusia punya kemampuan untuk
memanggil-ulang dirinya kembali dari masa lalu. Jadi ada daya untuk memungut
kembali kekuatan-kekuatan yang dia pernah miliki. Itu sebenarnya potensi yang
laten. Tapi itu semua perlu dijenguk ke masa lalu, bukan sebagai bagian dari
romantika dan nostalgia, melainkan demi mengenang kembali potensi yang selama
ini kita tekan dan kita pendam. Kita telah memendam berbagai nilai luhur yang
kita miliki sejak ribuan tahun lalu. Nah, itu semua harus kita panggil ulang.
Caranya bisa bermacam-macam.
JIL: Apa yang bisa Anda lakukan sebagai
seniman untuk menjemput masa lalu itu?
Menerangkan
agar setiap simbol-simbol agama dan budaya jangan kita perdaya dan manfaatkan
untuk kepentingan sesaat, sektoral, per golongan. Yang terjadi sekarang, proses
pembendaan simbol-simbol atau reifikasi itu berlangsung begitu kuat. Kita telah
pula memiskinkan simbol agama, membekukannya dengan cara menggunakannya untuk
kepentingan yang sempit. Akibatnya, simbol-simbol itu keluar dari maknanya yang
klasik dan tradisional. Karena itu, kita perlu selalu mencerdaskan diri. Kalau
masyarakat di negeri ini bertambah cerdas, saya kira akan banyak yang tidak
mudah terpengaruh dan tertipu simbol-simbol. []