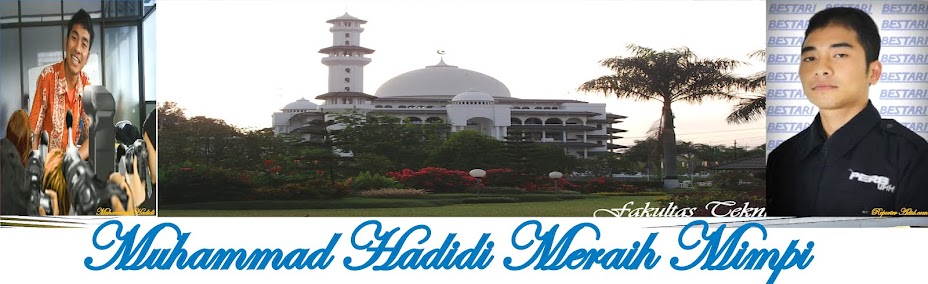بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
Oleh: Muhammad
Hadidi
Jurusan Syriah
Universitas Muhammadiyah Malang
Gender merupakan satu di antara
sejumlah wacana –yang bisa disebut- kontemporer yang cukup menyita perhatian
banyak kalangan, mulai para remaja, kalangan aktivis pergerakan, akademisi dan
mahasiswa, kalangan legislatif dan pemerintah, hingga para agamawan. Maksud
wacana ini adalah memutus ketidakadilan sosial berdasarkan perbedaan jenis
kelamin, selanjutnya berupaya mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan pada aspek sosialnya.
Dengan
masuknya wacana ini pada wilayah keislaman, maka para intelektual Muslim sudah
tentu tidak dapat begitu saja memproteksi diri dengan mengabaikan pembacaan
wacana ini. Meski tetap dengan pemahaman bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai
wacana, gender tetap dapat dibaca dari sudut pandang mana akan dimulai. Makalah
ini memberikan analisis atas bangunan wacana gender dalam kerangka menentukan
sikap dalam membaca dan berinteraksi dengan wacana ini.
A. Menelusuri Bangunan Wacana Gender
Pembicaraan tentang masalah gender
biasanya diawali dengan pembedaan secara ketat antara dua istilah, yaitu
“gender” dan “sex”. Kedua istilah ini memiliki makna yang sama: “jenis
kelamin”. Namun keduanya berbeda dalam konotasinya; sex berkonotasi natural dan
bersifat “given”, karenanya ciri-ciri yang dikandungnya merupakan ciri-ciri
biologis dengan segala sifat dan watak yang mengikuti ciri biologis itu, sedang
gender berkonotasi kebiasaan atau sifat-sifat sebagai human construction
atau social and cultural construction. Jika yang pertama, segala sifat
dan cirinya tidak bisa dipertukarkan, sedang pada yang kedua dapat
dipertukarkan.
Pembedaan semacam ini dianggap penting
karena sekalipun gender merupakan bidang pembicaraan yang kompleks,
kontrovesial, bahkan mengundang resistensi,[2]
namun wilayah kajiannya tetap dapat dibatasi, sekaligus dapat sebagai garis
ukur terhadap aliran pemikiran tertentu yang, bisa dikatakan, telah melewati
marka lalu lintasnya.
Hampir seluruh argumen dalam kajian
gender berawal dari suatu asumsi, bahwa perbedaan gender, bahkan
ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses
sejarah yang panjang dan dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi
secara sosial dan kultural, termasuk melalui tradisi keagamaan. Sebagaimana
sifat tradisi dan kebiasaan lainnya, proses panjang pembentukan gender, pada
umumnya juga sebagai suatu proses yang tidak disadari sehingga dianggap sebagai
sesuatu yang sifatnya natural, kodrati dan ketentuan Tuhan.[3]
Atas asumsi ini, wacana gender
kemudian terlibat dalam dua agenda sekaligus, pertama, melakukan
penelusuran tiada henti terhadap geneologi pembentukan tradisi yang disebutnya
sebagai patriarkal.[4]
Upaya ini, katanya, dalam rangka “menyadarkan” bahwa perbedaan dan
ketidaksetaraan gender itu benar-benar bersifat sosial dan kultural. Aplikasi
agenda ini, antara lain dengan maraknya upaya-upaya melakukan reinterpretasi
terhadap sumber, norma, atau apa saja yang menjadi dasar dari bangunan tradisi
dan budaya pada masyarakat tertentu. Kedua, melakukan perubahan; awalnya
perubahan persepsi, lalu pola pikir, dan akhirnya perubahan tradisi dan budaya
yang, menurutnya, berkeadilan gender.[5]
Agenda kedua ini, aplikasinya bisa hanya sekedar latihan-latihan keterampilan,
upaya pemberdayaan sampai lahirnya gerakan-gerakan keperempuanan (feminisme).
Dengan demikian gender bukanlah sekedar istilah,
tetapi merupakan konsep yang sarat nilai dan terkandung di dalamnya misi,
filosofi, dan bahkan ideologi tersendiri. Hal ini yang menurut penulis, para
pegiat gender di kalangan umat Islam Indonesia, kecuali hanya sedikit
dari mereka, pada umumnya tidak membekali diri dengan pemahaman tentang apa
akar-akar pemikiran gender dan bagaimana basis ‘ideologinya’. Sehingga yang ada
tidak lebih dari sekumpulan para wanita dengan beberapa kegiatannya sebagaimana
kelompok-kelompok wanita yang telah ada sebelumnya, seperti “dharma wanita”,
PKK, dll. Padahal sebagai pemikiran, gender bisa saja berbeda atau bertentangan
dengan tradisi dan budaya mereka. Atau, di lain pihak malah melakukan tuntutan
kebebasan pada beberapa aspek kehidupan, misalnya dalam politik, ekonomi, seni,
dll., dengan dalih kesetaraan gender. Sehingga gender hanya digunakan sebagai
“tempat berlindung” atau sebagai “atas nama”. Tampaknya, kondisi demikian yang
membuat gender memiliki semakin banyak makna konotasinya, sekaligus membuat
watak aslinya menjadi dikaburkan.
Maka membaca wacana gender
perlu melakukan penelusuran terhadap akar-akar yang membangunnya. Berikut ini
disampaikan beberapa anasir yang menggambarkan perjalanan wacana ini sampai
hari ini.
1.
Gender sebagai gerakan
Di sini, gender dalam pengertiannya
sebagai gerakan keperempuanan (feminisme). Wilayah ini menjadi garapan pegiat
feminisme yang biasanya membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) atau
organisasi, baik mandiri ataupun berafiliasi dengan ormas tertentu atau dengan
lembaga-lembaga pemerintah. Kegiatan yang dilakukan, pada umumnya mengambil
salah satu atau beberapa dari bidang berikut ini: penelitian,
penyuluhan, produksi ide, gerakan utk kesehatan reproduksi, advokasi
atas kekerasan perempuan, pelatihan-pelatihan, peningkatan pendidikan, dll.
Meski terkadang tampak memiliki kesamaan bidang
kegiatan, namun LSM Feminis ternyata terdiri dari beberapa karakter, bisa
dikatakan, tergantung pada ‘basis ideologi’ yang dianut. Ada sejumlah aliran besar feminisme yang
selama ini menjadi kiblat LSM-LSM itu, yaitu: aliran feminisme liberal,
feminisme kultural, feminisme radikal, dan feminisme sosialis.[6]
Feminisme liberal, dalam perjuangannya
menekankan pada hak-hak sipil kaum perempuan. Aliran ini juga memandang bahwa
kaum perempuan bebas mengambil keputusan atas seksualitasnya dan hak reproduksi
mereka. Lalu feminisme kultural yang juga disebut feminisme reformatif dan
feminisme romantis. Aliran ini lebih mengaitkan nilai kehidupan dengan nilai
tradisional perempuan, seperti bela rasa, pengasuhan, pengelolaan lingkungan
hidup, dan nilai kemanusiaan yang menekankan moral. Feminisme radikal menekankan
penghapusan merajalelanya dominasi laki-laki terhadap kehidupan. Dimulai dari
dominasi laki-laki terhadap perempuan, kemudian muncul berbagai dominasi
berbasis kekuasaan. Sedangkan, feminisme sosialis menekankan perhatiannya pada
persoalan dominasi laki-laki kapitalis berkulit putih dalam perjuangan keadilan
ekonomi global.
Di samping itu, terdapat beberapa aliran baru yang
cukup berpengaruh, seperti feminis spiritualis, ekofeminis, dll. Feminis
spiritualis
sebenarnya merupakan peneguhan pandangan kaum feminis radikal. Menurut mereka,
spiritualitas itu bersifat eksperiensial (berbasis pengalaman), ia bukanlah
teori abstrak melainkan realitas yang dihidupi secara personal. Pertumbuhan
spiritualitas feminis tidak terjadi secara gaib, tetapi berproses secara sadar
dan oleh karena itu melalui pergumulan pada setiap pribadi. Sedang ekofeminis
mengkaitkan keprihatinan perempuan atas gencarnya pembangunan namun merusak
lingkungan hidup, khususnya lingkungan alam.
Untuk kasus Indonesia, sebagaimana beberapa
pengamat gender, aliran yang paling dominan adalah feminisme libaral. Dominasi
aliran ini seiring dengan gejala liberalisasi global, yang akan memberi
kesempatan untuk perdagangan bebas. Jika dirunut lebih jauh, liberalisasi ini
merupakan bagian dari faham kapitalisme.[7]
Peningkatan peran perempuan pada berbagai sektor, berarti menambah peluang
pasar.
Kapitalisme, ideologi besar ini yang
selalu bersaing dengan sosialis-Marxis. Bagi orang-orang Marxis, terdapat
asumsi jika keadilan sudah diwujudkan dalam masyarakat, apalagi masyarakat
tanpa kelas, maka dengan sendirinya semua masalah yang dimunculkan akibat
ketidaksetaraan akan teratasi. Classless society akan memunculkan genderless
society. Demikian kira-kira cara berfikir feminisme Marxis.
Pembicaraan ini tidak sampai
menguraikan bagaimana sejarah pertumbuhan feminisme liberal, yang konon, tumbuh
pertama kali di Amerika yang cikal bakalnya sudah dimulai sejak tahun 1800-an.
Namun paling tidak, ada cukup punya alasan jika ada penolakan terhadap
pemikiran gender.
Satu catatan yang dapat kita buat,
bahwa pada aspek ini problem gender tampak telibat resistensi politis, bahkan
terlibat pada gerakan fisik. Inilah yang oleh kaum feminis disebut dengan
gelombang pertama feminisme.
2.
Gender sebagai diskursus kefilsafatan
Anasir ini, banyak yang menyebutnya
sebagai bagian terpenting dari wacana gender. Namun anasir ini juga yang paling
tidak disadari oleh para pegiat atau para “jurkam” gender pada umumnya.[8]
Dalam konstruksi teoritis feminisme, masuknya persoalan gender ke dalam
diskursus filsafat ini, sering disebut gerakan feminisme pada gelombang kedua.
Sebagai bagian dari diskursus
kefilsafatan, gender sudah tentu memiliki sifat dan karakteristik sebagaimana
kajian filsafat pada umumnya. Problem kefilsafatan merupakan problem
kemanusiaan (human construction). Sasaran kajian filsafat adalah pola
pikir manusia. Maka filsafat adalah ilmu tentang pola pikir manusia. Jika dalam
gender, disebut-sebut perempuan sebagai objek wilayah kajiannya, maka yang
sebenarnya terjadi, gender tidak pernah menyentuh objeknya secara langsung.
Sebagai diskursus kefilsafatan, objek kajian gender adalah pola pikir manusia
tentang perempuan, bukan para perempuan itu sendiri.
Pandangan ini juga menunjukkan bahwa
jika gender menginginkan perubahan maka perubahan yang dimaksud adalah
perubahan pola pikir, meskipun endingnya juga pola pikir kolektif (masyarakat).
Pada wilayah ini, gender memang bisa dikatakan kawasan elitis; hanya menjadi
pembicaraan kaum terbatas, yakni mereka yang memiliki ketertarikan terhadap
kajian kefilsafatan.
Dari perspektif ini, kemunculan gender
sebagai bagian dari diskursus kefilsafatan tidak dapat dilepaskan dari semangat
pemikiran POSMO. Wacana gender, bahkan dikatakan, mendapati basis
kefilsafatannya dari pemikiran ini. Maka beberapa filsuf yang berada di bawah
panji POSMO memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap wacana gender ini,
seperti Michel Foucault dengan discoursenya, Jacques Derrida dengan deconstructionnya, dll.
Setidaknya ada empat tema besar dalam
pemikiran posmodern, yaitu semangat relativitas, dekonstruksi, rekonstruksi dan
pluralitas. Kaitannya dengan gender, tema relativitas digunakan untuk ‘memecah’
teka teki bahwa apapun yang sifatnya human construction adalah relatif,
termasuk budaya patriarki. Oleh karena itu, tidak ada halangan untuk dilakukan
pembongkaran untuk menemukan asal-usul (geneologi), sumber dan akar-akar budaya
ini. Upaya inilah yang, oleh mereka, disebut dekonstruksi.
Dekonstruksi atas akar-akar budaya
patriarki memang hanya merupakan "sasaran antara", karena setelah
itu, dengan leluasa melakukan eksperimen, yang disebutnya dengan upaya
rekonstruksi: menata kembali budaya yang tidak pilih-pilih kasih, budaya yang
berkeadilan gender. Meski tetap dengan kesadaran bahwa masing-masing suku, bangsa,
tradisi memperoleh hak yang sama dalam apresiasi atas makna keadilan gender,
sehingga tidak ada paksaan dari satu tradisi kepada tradisi lainnya.
Masing-masing tradisi diberikan eksistensi dalam memaknai “kesetaraan gender”.
Pemahaman semacam ini yang mereka sebut dengan pluralitas. Inilah keterkaitan
isu gender dengan pemikiran POSMO.[9]
Pada tataran ini, kiranya juga cukup
wajar jika kalangan agamawan merasa keberatan atas merebaknya isu gender, yang
umumnya meyakini bahwa tradisi (keagamaan) adalah suatu tatanan yang dibangun
di atas nilai-nilai agama. Namun atas
nama gender, tradisi itu lalu dibongkar begitu saja.
Pemikiran lain yang juga bisa
dikatakan pemberi energi atas wacana gender adalah pemikiran New Left
dan khususnya dari Habermas. Refleksi filsafat Habermas terkumpul dalam istilah
Critical Theory (teori kritis). Sesuai dengan istilahnya, inti dari
teori ini adalah ‘kritik’ yang disebutnya sebagai self reflection. Atas
teorinya ini, Habermas dianggap berhasil meletakkan dasar-dasar bagaimana
membaca dan memaknai sejarah dan tradisi, serta melakukan reinterpretasi.[10]
Dengan self reflectionnya,
Teori Kritis mengajak untuk terjaga dari ‘tidur’ dan bersikap kritis di tengah
dunia-kehidupan, tradisi dan sistem masyarakat, serta melakukan ‘penyegaran’
terhadap kebekuan budaya. Karena, jika tidak kritis terhadap tradisi, maka akan
jatuh pada ketidaksadaran. Dalam kondisi demikian, bisa saja suatu ideologi
tertentu (atau kepentingan tertentu) sengaja memanfaatkan kesempatan dalam
kesempitan untuk meninabubukkan masyarakat, dan akhirnya mengeksploitasi dan
melakukan tindakan oppressive.
Dalam pandangan Teori Kritis, selama
ini ilmuwan dan masyarakat umumnya menganggap sejarah dan tradisi sebagai
sesuatu yang taken for granted, sebagai sesuatu yang memang demikian
adanya. Mereka tidak kritis, tidak lagi mempertanyakan, mana yang natural
dan mana yang memang human construction atau social construction.
Bagi Teori Kritis, ilmuwan tidak cukup jika hanya duduk di belakang meja kerja
sibuk membangun teori, sementara tidak memiliki kepakaan terhadap problem
sosial masyarakatnya. Sebaliknya, para ilmuwan harus terlibat dalam praktek,
bahkan kegiatan keilmuan tak lain dari praktek itu sendiri. Mereka harus dekat
dan berkomunikasi dari hati ke hati dengan masyarakat luas.
Berbeda dengan Old Left yang
memanfaatkan proletariat kaum buruh sebagai subjek perubahan, Teori Kritis
justru menggunakan kalangan intelektual dan ilmuwan untuk mengadakan perubahan.
Bagi Habermas, tidak mungkin mengharapkan kaum buruh proletar sebagai subjek
perubahan (revolusi), karena kesadaran kelas mereka hilang, terintegrasi pada
sistem kesadaran kapitalis. Oleh karena itu, jika ingin terdapat perubahan
struktur di dalam masyarakat, ilmuwan dengan masyarakat komunikasi yang
dibangun, harus terus melakukan komunikasi, diskusi-diskusi bebas, dan
membangun wacana serta yang terpenting melakukan praksis emansipatoris.
Dari sinilah, yang menurut penulis,
untuk di Indonesia terlahir tokoh-tokoh feminis seperti Wardah Hafidz, Gadis
Arivia, Karlina Leksono, Ayu Utami, Lies Mascoes Natsir, Wilasih Noviana, dll. Mereka adalah ilmuwan dan sekaligus
aktivis pergerakan.
3.
Dari isu sosial ke isu keagamaan
Sosiolog
Emile Durkheim dalam suatu karyanya pernah menyatakan: “…that nearly all the
great social institutions were born in religion…. If religion gave birth to all
that is essential in sociaty, that is so because the idea of sociaty is the
soul of religion.”[11]
Pernyataan Durkheim ini, dengan tanpa mendiskusikannya pada wilayah teologis,
menunjukkan sedemikian kuatnya peranan dan posisi agama dalam tatanan kehidupan
sosial. “Hampir semua peradaban besar yang pernah tumbuh di muka bumi pada
mulanya dimotivasi oleh keyakinan agama”, demikian pernyataan Dr. Komaruddin
Hidayat dalam pidato pengukuhan guru besarnya[12]
Pernyataan
Durkheim dan Komaruddin Hidayat di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara
wilayah sosial dan agama. Artinya, dalam hal ini, seberapapun masalah sosial
itu tetap akan memiliki ketersinggungan dengan masalah agama, tidak kecuali
masalah gender.
Dalam
kajian gender, yang dianggap sebagai penyulut pemikiran dan gerakan gender
adalah sebuah karya 'The Feminine Mystique' yang ditulis oleh Betty Friedan,
yang penerbitannya mengambil momen reformasi di Amerika Serikat tahun 1963.
Buku itu berdampak luas, lebih-lebih setelah Betty Friedan membentuk organisasi
wanita bernama 'National Organization for Woman' (NOW) di tahun 1966, yang
gemanya kemudian merambat ke segala bidang kehidupan. Dalam bidang
perundang-undangan, tulisan Betty berhasil mendorong dikeluarkannya 'Equal Pay
Right' (1963) sehingga kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih
baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan
'Equal Right Act' (1964) di mana kaum perempuan mempunyai hak pilih secara
penuh dalam segala bidang.
Gerakan
feminisme berjalan terus, dan di tahun 1967 dibentuklah 'Student for a
Democratic Society' (SDS) yang mengadakan konvensi nasional di Ann
Arbor, kemudian dilanjutkan di Chicago pada tahun yang sama. Dari sinilah
mulai muncul kelompok 'feminisme radikal' dengan membentuk 'Women's Liberation
Workshop' yang lebih dikenal dengan singkatan 'Women's Lib'. Dalam pandangan
Women's Lib, peran kaum perempuan dalam hubungannya dengan kaum laki-laki dalam
masyarakat kapitalis terutama Amerika Serikat tidak lebih seperti hubungan yang
dijajah dan penjajah. Sehingga di tahun 1968 kelompok ini secara terbuka
memprotes diadakannya 'Miss America Pegeant' di Atlantic City yang mereka
anggap sebagai 'pelecehan terhadap kaum wanita' dan 'komersialisasi tubuh
perempuan.' Gema 'pembebasan kaum perempuan' ini kemudian mendapat sambutan di
mana-mana di seluruh dunia.
Demikianlah,
isu yang dibawa pemikiran gender pada awal sejarahnya adalah isu sosial. Gender
dibangun atas keprihatinan terhadap masalah sosial, terutama pada masyarakat
yang menempatkan perempuan pada posisi rendah, suatu hal yang tidak terjadi
pada masyarakat muslim. Karena Islam menempatkan perempuan dan kaum ibu pada
posisi yang terhormat.[13]
Pada
awalnya, bangkitnya gerakan kaum perempuan itu mendapat banyak simpati bukan
saja dari kaum perempuan sendiri tetapi juga dari banyak kaum laki-laki, tetapi
perilaku kelompok feminisme radikal yang bersembunyi di balik 'women's
liberation' telah melakukan usaha-usaha yang lebih radikal yang berbalik
mendapat kritikan dan tantangan dari kaum perempuan sendiri dan lebih-lebih
dari kaum laki-laki. Organisasi-organisasi agama kemudian juga menyatakan
sikapnya yang kurang menerima tuntutan 'Women's Lib' itu karena mereka kemudian
banyak mengusulkan pembebasan termasuk pembebasan kaum perempuan dari agama dan
moralitasnya yang mereka anggap sebagai kaku dan buah dari 'agama patriachy'
atau 'agama kaum laki-laki.'
Upaya
gender memasuki wilayah agama ini membuat persoalan menjadi bertambah dan semakin
kompleks. Karena pada umumnya, gender (atau ketidakadilan gender) lalu dianggap
sebagai benar-benar masalah agama. Sehingga tradisi dan khazanah keagamaan
dipertanyakan ulang. Awalnya memang dilakukan oleh kaum liberalisme kristen
terhadap agama mereka sendiri, namun di Islam ternyata juga terpengaruh dan
ikut-ikutan.
Di
Islam umpamanya, ketika melihat fiqih dan tafsir yang dianggapnya bias gender,
dikatakan sebagai "ketelodoran" utama fiqih Islam dan tafsir Al Quran
konvensional. Para ulama fiqih pada periode awal telah "lengah" dalam
menafsirkan ayat-ayat gender dalam Al Quran. Mereka hanya memahaminya secara
literal. Akibatnya, hukum Islam saat ini dituduh telah menindas kaum perempuan,
dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat kelas dua.
Ketersinggungan
masalah gender dengan tradisi keagamaan, ternyata bukan hanya sebab kegamangan
para agamawan atas derasnya isu-isu sosial, namun ‘fakta’ sejarah telah
menunjukkan bahwa gender telah mengambil wilayah agama secara signifikan.
Dengan
masuknya gender menjadi problem keagamaan seperti itu, wacana gender berarti
mamasuki babak baru yang oleh aktivis feminis disebut gelombang ketiga
feminisme. Pada babak ini, kesetaraan gender menjadi pertimbangan utama dalam
setiap isu dan pemikiran keagamaan, termasuk isu moral dan pemikiran teologi.
Sekalipun banyak ragamnya, pemikiran demikian kemudian melahirkan apa yang
disebut dengan teologi feminis.
4.
Gender sebagai pendekatan dalam studi
agama
Para
peminat kajian agama (religious studies) melihat bahwa isu gender merupakan
persoalan global, sehingga agama-agama di dunia harus angkat bicara atas isu
ini. Disiplin ini juga akan membuktikan seberapa besar concern agama
terhadap persoalan gender dan dalam memberikan solusi atas problem diskriminasi
terhadap perempuan dalam kehidupan berbudaya dan bermasayarakat. Secara lebih
jauh, religious studies melihat problem gender sebagai upaya
mempertemukan agama-agama.
B. Gender dan Dekonstruksi Syari'ah
Dalam kaitannya
dengan pemikiran dan keilmuan Islam, "dekonstruksi syari'ah"
merupakan agenda tak terpisahkan dari wacana gender ini, di samping
agenda-agenda yang lain. Agenda ini dimulai dengan asumsi bahwa pemikiran dan
keilmuan Islam serta kitab-kitab keilmuan Islam hampir semuanya dikarang oleh
laki-laki, sehingga bias gender, prasangka dan kepentingan jenis
laki-laki boleh jadi sangat mewarnai pembahasanya. Katanya, seandainya
pakar-pakar keislaman itu perempuan dan dapat mengembangkan sebuah pemikiran keislaman, meskipun berdasarkan
nash yang sama, boleh jadi
hasilnya sangat berbeda dengan pemikiran yang ada sekarang ini.
Asumsi ini tampaknya muncul setelah mereka
melihat apa yang sebelumnya telah dilakukan oleh para ahli teolog perempuan Kristen.
Melalui kajiannya terhadap karya-karya
kaum teolog laki-laki mereka berhasil
membongkar banyak prasangka dan bias yang
sebetulnya tidak bersangkut paut
dengan ajaran agama yang asli tetapi yang belakangan dianggap sebagai bagian yang esensial dari doktrin-doktrin
Kristen. Para teolog feminis telah mengembangkan suatu teologi Kristen
alternatif yang berbeda sekali daripada ajaran tradisional yang begitu
paternalis dan menindas perempuan.
Dalam dunia Islam, Riffat Hassan,
sarjana dari Pakistan, adalah salah seorang
yang berusaha mengembangkan pemikiran Islam yang, dikatakan, bersih dari bias laki-laki.[14] Lalu muncul buku Perempuan dan Islam,
Kajian Sejarah dan Teologi oleh
Fatima Mernissi,[15] seorang
sarjana dari Maroko yang kemudian disebut sebagai teolog feminis muslim.
Dalam kajiannya ia mulai mempertanyakan hal-hal yang diajarkan kepadanya
mengenai status dan tingkah laku yang
layak bagi kaum Muslimat. Ia mengkaji kitab Hadits, tafsir dan sirah untuk mencari asal usul dari –apa yang
disebutnya dengan- misogini, kebencian
terhadap perempuan, dalam tradisi Islam. Ia menunjukkan, berdasarkan sumber Islam masa awal, sikap Nabi
terhadap perempuan sangat arif,
terbuka, dan toleran, tetapi belakangan muncul tokoh dalam umat yang punya
sikap hampir bertolak belakang dengan sikap Nabi itu. Pemimpin yang ia soroti sebagai orang yang
bertanggung jawab atas penurunan
status wanita dalam Islam adalah Khalifah Umar yang, katanya, muncul lebih macho dalam sumber-sumber sejarah, lebih keras dan
menindas terhadap perempuan.
Sementara dalam
menyoroti para perawi hadits, Abu Hurairah mendapat perhatian utama karena banyak Hadits
yang memojokkan perempuan konon dirawikan oleh Abu Hurairah. Dari hal-hal yang
diketahui mengenai riwayat hidup Abu
Hurairah, Mernissi menggambarkan profil psikologi, tokoh ini sebagai
laki-laki yang mengalami kesulitan menghadapi perempuan, mungkin juga kelainan seksual.
Berdasarkan pengamatannya, Mernissi
melihat para pengarang kitab-kitab klasik
memang bertolak dari asumsi superioritas laki-laki atas perempuan. Kecuali itu ia juga melihat membanjirnya edisi baru dari kitab-kitab klasik yang paling
diskriminatif terhadap perempuan, dengan harga yang
sangat murah di pasaran. Bagi Mernissi, itu bukanlah suatu yang kebetulan,
bahkan, katanya, telah terjadi serangan massal dari kalangan ulama paling konservatif yang ingin melestarikan status
quo dan "melindungi"
Islam dari "bahaya" emansipasi perempuan dan feminisme.[16]
Persoalan lain yang terus diangkat oleh pegiat gender
adalah problema seputar budaya Arab atau budaya Islam. Misalnya dipertanyakan:
apakah ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan hanya bagian dari budaya kitab klasik saja, ataukah memang inheren dalam Islam? Apakah jilbab dan larangan perempuan keluar dari rumah hanya berdasarkan
salah satu di antara sekian banyak
interpretasi Islam, atau perintah mutlak Tuhan.
Dalam suatu tulisan yang meninjau hukum-hukum fiqih
mengenai perempuan, orientalis
terkenal Hamilton A.R. Gibb dengan nada menyesal mengatakan bahwa bagian fiqih ini tidak didasarkan atas
uraian Al Quran melainkan atas Hadits-Hadits
yang mencerminkan adat suku-suku Arab.[17] Ia menunjukkan bahwa hampir setiap hukum Al
Quran mengenai perempuan merupakan perbaikan hak dan statusnya dan penolakan
adat suku-suku Arab yang sangat tidak
menguntungkan kaum perempuan. Dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya, demikian kesimpulan
Gibb, para ahli fiqih ternyata lebih
dipengaruhi oleh adat (terutama konsepsi tradisional tentang
'ird, kehormatan suku) daripada
ketentuan Al Quran.[18] Menurut Gibb, ijtihad Khalifah 'Umar yang membolehkan laki-laki mengucapkan
talak tiga sekaligus, adalah
upaya membatalkan perlindungan yang diberikan kepada perempuan oleh Al
Quran dan mengembalikan hukum adat yang membolehkan
laki-laki untuk segera melepaskan istrinya, tanpa alasan.
Pengamatan seperti ini, di
kemudian hari terbukti mendorong pemikir Islam untuk meninjau kembali Al Quran dan Hadits yang disebutnya mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan. Hadits-Hadits yang diakui secara umum pun
(misalnya, yang dalam al-Kutub as-Sittah) juga ditinjau untuk menyaring Hadits
yang dikatakan walaupun atasnama Nabi namun melestarikan adat-adat pra-Islam. Upaya inilah yang dilakukan oleh
Fatima Mernissi. Usaha Mernissi ini kemudian menimbulkan kontroversi, dan banyak pihak lalu
menyebutnya sebagai "Inkarussunnah".
Bagi penganut gender, masih terdapat beberapa ayat Al Quran yang dengan jelas menyatakan ketidaksamaan hak, misalnya dalam hal warisan, meskipun juga diakui
bahwa secara umum Al Quran telah memberikan
banyak hak dan kebebasan kepada perempuan yang tidak
pernah dimiliki dalam budaya Arab Jahiliah.
Pertanyaan mereka selanjutnya
adalah: apakah itu berarti bahwa superioritas laki-laki atas
perempuan harus diterima sebagai ajaran Islam yang mutlak dan tidak bisa diubah? Maka
dimulailah melakukan upaya penafsiran terhadap ayat-ayat terkait yang
disebutnya dengan "penafsiran kontekstual",
sebuah upaya memahami ayat-ayat
ahkam dalam konteks masyarakat Madinah pada zaman Nabi dan menerapkan semangat hukumnya daripada hukum-hukum yang harfiah. Salah satu pendobrakan radikal adalah pendekatan Munawir Syadzali, yang menyatakan bahwa pembagian warisan memerlukan modifikasi untuk masyarakat yang punya struktur sosial lain daripada Madinah tiga belas abad yang lalu.
Beberapa negara Muslim sekular seperti Turki dan Tunisia adalah termasuk negara yang mengabaikan
masalah kontektualisasi (atau dalam bahasa munawir Sadzali: reaktualisasi) ini.
Undang-undang perkawinan dan undang-undang lainnya hanya
didasarkan pada hukum sipil seperti
di negara Barat tanpa usaha
mencari legitimasi Islam. Situasi ini, tentu saja, menyebabkan sebagian umat di sana merasa teralienasi dari
negara dan boleh jadi menimbulkan
gerakan "fundamentalis" yang kuat. Melihat arus perkembangan dalam dunia Islam masa kini,
sekularisme tidak merupakan alternatif
yang potensial. Pertanyaan apakah hak-hak perempuan dan hak-hak asasi manusia lainnya yang tercantum dalam
perjanjian internasional[19] itu bertentangan dengan Islam.
Perkembangan umat Islam di
negara sekular itu kemudian dijadikan alasan bagi pembenaran upaya "pembaruan" pemikiran Islam secara sangat radikal. Adalah Abdullahi Ahmed An-Na'im, sarjana hukum dari Sudan, yang disebut-sebut melakukan upaya ini
dengan bukunya: Menuju Suatu
Reformasi Islami.[20] Dalam bukunya itu, An-Na'im
menyampaikan beberapa usul pembaruan berdasarkan pemikiran gurunya, Mahmud Muhammad Taha.
Mahmud Taha bertolak dari
perbedaan yang terdapat antara surat-surat yang turun di Mekah dan di Madinah. Surat-surat Makiyyah bersifat peringatan moral, egalitarian, dan universal, sedangkan surat-surat Madaniyyah lebih bersifat spesifik dan kontekstual.
Beberapa ayat Madaniyyah kelihatannya bertentangan
dengan ayat-ayat Mekah, dan itu yang melahirkan teori nasikh
dan mansukh: menurut para ahli tafsir dan fiqih, terdapat ayat yang membatalkan ayat lain. Status
perempuan (dan juga status minoritas non-Muslim) diatur oleh ayat-ayat Madaniyyah yang membatalkan ayat-ayat Makiyyah yang
lebih egaliter.
Dengan sangat berani Mahmud Taha menyatakan bahwa sekarang sudah
waktunya untuk memutarbalikkan nasikh dan mansukh itu. Perintah Tuhan yang punya relevansi universal adalah tercantum dalam
surah-surah Makiyyah. Karena masyarakat Arab pada zaman Nabi belum sanggup
melaksanakan semua perintah itu,
lalu turunlah ayat-ayat yang lebih sesuai dengan situasi zaman itu, dan untuk
sementara membatalkan ayat-ayat yang lebih universal dari Mekah. Masyarakat
sekarang sudah lebih dewasa, dan tidak ada alasan lagi untuk membatalkan
perintah Tuhan pertama yang egaliter. Ayat-ayat yang dulu dianggap nasikh
sekarang sudah layak menjadi mansukh.[21]
C. Bagaimana Membaca Wacana Gender
Begitulah,
dalam kaitannya dengan pemikiran keislaman, gender telah mengambil wilayah
secara cukup signifikan. Pembongkaran terhadap khazanah Islam memang bukan
persolan yang kebetulan, tetapi sebuah agenda dan proyek besar mereka. Padahal
dari sisi keilmuan sekalipun, semua itu merupakan karya terbaik anak sezaman.
Beberapa
hal ini membuat semakin jelas bahwa gender memang bukan hanya sekedar kata atau istilah, tetapi merupakan konsep
yang mengandung misi, filosofi, dan ideologi. Gender ternyata bukan merupakan
bahasa awam yang sederhana, tetapi merupakan ‘eksperimen’ pemikiran karena
posisinya sebagai diskursus kefilsafatan. Gender bukan hanya suatu pemikiran
yang menjadi konsumsi para akademisi, tetapi ia juga merupakan gerakan (saya
kira, gerakan yang beragam sesuai dengan tuntutan dan motivasinya). Gender juga
bukan sekedar isu sosial, tetapi ia sudah mengambil wilayah keagamaan secara
signifikan.
Dilihat
dari sisi sumber dan akar-akarnya, gender jelas merupakan konsep asing yang
tidak serta merta bisa disebut sebagai gejala global yang terjadi pada seluruh
tradisi yang ada di dunia ini. Meski demikian, ibarat barang dagangan, gender
bisa dikatakan sebagai sebuah produk yang dikemas khusus sehingga menarik minat
untuk membelinya, tidak saja bagi yang punya uang, tetapi juga bagi yang hanya
kebetulan melihatnya, meski belum tahu apa isinya.
Perguruan Tinggi Islam, dengan
seluruh para intelektual di dalamnya, sesuai dengan identitas yang
disandangnya, yakni dunia akademis namun Islami atau lembaga Islam namun
akademis, kiranya tidak dapat begitu saja lepas tangan, melakukan upaya
proteksi dari isu-isu yang bisa digolongkan kontemporer itu. Namun juga tidak
bijaksana jika liberalisme dibiarkan ‘liar’ hanya atas nama akademis. Sama
tidak bijaksananya jika isu-isu kontemporer itu dibicarakan namun akar-akar dan
sumber pemikirannya dinafikan. Sikap demikian, di samping tidak akademis, juga
bisa berarti menyembunyikan bagaimana jati diri sebenarnya wacana itu, yang
jika saja jati diri itu ditunjukkan belum tentu ada orang yang meminatinya,
atau paling tidak mereka akan pikir-pikir dulu.
Maka
membaca wacana gender mesti dilakukannya secara kritis dan analitis[22],
dengan menempatkannya sebagai wacana (discourse). Upaya ini dimaksudkan untuk
menghindari pembacaan yang hanya sampai pada permukaan, sebaliknya dapat
mengantarkannya untuk sampai pada sumber dan akar wacana. Karena, menurut
Foucault, setiap discourse pasti mempunyai geneologi dan dapat ditemukan
asal usul pembentukannya.
Sekalipun
demikian, bagi perguruan tinggi Islam, membaca wacana gender jelas bukan hanya
sebagai sarana melatih keterampilan analisis terhadap masalah-masalah sosial.
Apalagi secara serta merta melibatkan diri dalam diskursus dan aksinya,
layaknya sebagai barang baru yang jika tidak diikutinya, takut disebut sebagai
ketinggalan wacana. Namun dengan basis keislaman yang kuat, memposisikan ajaran
Islam dan khazanah keislaman sebagai tolak ukur dan pijakan dalam setiap
pilihan sikap, termasuk dalam melakukan proses analisisnya.
Harus
diakui, produk-produk pemikiran asing yang berkembang satu atau dua dasa warsa
belakangan ini, mengejutkan umat Islam, lebih khusus lagi kaum akademisi Islam.
Dan yang lebih mengejutkan lagi, bahwa sikap umat Islam terhadap pemikiran asing
itu cukup beragam. Kondisi demikian mengharuskan untuk menyadari akan arti
penting membangun sejarah dan peradaban Islam dengan melihat kembali khazanah
keislaman masa lalu dan menangkap pesan-pesan itu dengan suatu kesadaran
kreatif, namun tetap tidak keluar dari pandangan hidup (weltanschauung)
keislaman.[23]
Dalam
Islam, mendalami ajaran agama (tafaqquh fiddin) jelas merupakan
kewajiban bagi setiap umatnya; laki-laki ataupun perempuan. Mengangkat harkat
dan martabat kemanusiaan, termasuk kaum perempuan, adalah tuntunan agama.
demikian juga, melakukan pemberdayaan kaum wanita dan meningkat taraf
kesehatan, kecerdasan, dan meningkat peran mereka dalam kehidupan
bermasyarakat. Sebaliknya menjatuhkan harkat dan mertabat kemanusiaan merupakan
larangan agama, ada atau tanpa konsep gender. Maka kritis terhadap konsep
gender bukan berarti memandang rendah terhadap kaum perempuan atau membiarkan
ketidakadilan terhadap mereka dan berhenti melakukan pemberdayaan. Tetapi,
sekali lagi, merupakan pilihan sikap yang menempatkan ajaran Islam sebagai
tolak ukur dan batu ujian terhadap keabsahannya.
Kritis
terhadap konsep gender, bahkan juga bukan berarti penolakan secara membabi buta
terhadap konsep itu. Karena, sebagaimana terlihat dalam sejarahnya, persoalan
gender muncul dari suatu tradisi dan budaya yang memang menempatkan perempuan
pada posisi rendah.[24]
Bukti adanya tradisi demikian, tidak hanya disebutkan dalam sejarah tetapi juga
dalam nash Al Quran, yang mengkisahkan suatu masyarakat yang merasa rendah jika
terlahir dari keluarga mereka, anak-anak perempuan, maka anak itu harus
dibunuhnya. Artinya, bagi suatu tradisi atau budaya, yang masyarakatnya tidak
memandang rendah jenis yang satu terhadap jenis yang lain, maka gender bukan
lagi menjadi masalah, atau paling tidak cukup sebagai wacana.
Pada
tahap terakhir, membaca wacana gender harus dengan meletakkannya pada konteks
yang lebih luas atau bahkan global. Upaya ini dimaksudkan agar tidak ‘terlalu’
terjebak pada diskursusnya dan melakukan analisis dengan lebih objektif. Yang
kita maksud dengan konteks yang lebih luas di sini adalah pola pikir
modernitas-Barat. Jika disebut misalnya, perempuan dijadikan budak, ternyata
laki-laki pun banyak yang dijadikan budak, bahkan juga anak-anak, sekalipun
kebanyakan oleh kaum lelaki. Maka mengangkat isu gender sebagai solusi atas
kehidupan yang eksploitatif seperti itu, tentu hanya tambal sulam, kalau tidak
malah salah sasaran. Karena, yang sebenarnya terjadi adalah proses dehumanisasi
yang berakar pada pola pikir modern, yang formalis-instrumentalis, materialis, physically,
dll. Pola pikir ini telah menjadi semacam monster besar yang hampir-hampir
tidak mungkin untuk dihindari.
Proses
penghilangan unsur-unsur kemanusiaan ini tampaknya sudah merasuk ke hampir
seluruh aspek kehidupan ini. Pola hubungan guru-murid, anak-ortu, bos dan anak
buahnya, pimpinan dan bawahan, bahkan hubungan suami dan istri, semuanya
menjadi semacam hubungan robotik. Maka wajar jika kekerasan dapat terjadi di
mana-mana, termasuk yang terkait dengan perempuan.
Dengan
kesadaran semacam ini, maka dapat
dipahami jika dewasa ini juga marak gerakan-gerakan moral, gerakan spiritual,
dan gerakan kemanusiaan lainnya. Karena memang merupakan momentum bagi mereka.
Dengan
demikian, setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam membaca wacana
gender. Pertama, menempatkan Islam dan ajaran Islam sebagai pijakan dan
tolak ukur dalam bersikap dan dalam melakukan proses analisis. Kedua,
memperlakukan gender sebagai wacana atau discourse, sehingga
analisis-kritis yang dilakukannya menjangkau sampai pada akar dan sumber
pembentukannya. Ketiga, menempatkan problem gender sebagai suatu kasus
spesifik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat kejelasan bahwa pada tradisi dan
masyarakat yang selama ini telah menempatkan perempuan pada posisi terhormat,
gender bukan lagi manjadi masalah. Sebaliknya, gender bisa jadi menjadi problem
besar, jika memang terdapat tradisi dan budaya yang menempatkan perempuan pada
posisi rendah, terjajah, dst. Keempat, meletakkan problem gender pada konteks
yang lebih luas.
D. Akhirul Kalam
Melakukan
kajian terhadap konsep-konsep asing dan lebih khusus lagi konsep Barat, memang
tidak mesti dapat aman dari keterpengaruhannya, namun juga bukan berarti sama
sekali tidak memiliki nilai manfaat. Paling tidak dapat mengingatkan kita,
membuat kita terjaga, dan memikirkan apa-apa yang selama ini tak terpikirkan,
menanggapi dan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang telah lama tidak
kita anggap sebagai masalah. Maka mendahulukan prejudice bukan saja tidak ilmiah
tetapi juga kontraproduktif. Yang dibutuhkan di sini adalah kemampuan bermain
seni, yaitu seni memilah-milah mana yang bermanfaat dan mana yang tidak
bermanfaat, seni mengambil yang bermanfaat dan membuang jauh-jauh yang tidak
bermanfaat.
Dalam
Islam, pemberdayaan wanita muslimah dan perempuan pada umumnya jelas merupakan
bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas ketaqwaan dalam makna
yang seluas-luasnya; ada atau tidak ada konsep gender, dan tentu saja bukan atas
nama gender. Satu hal perlu diperhatikan bahwa gender bukanlah sekedar kata
atau istilah tetapi merupakan konsep yang terkandung di dalamnya misi,
filosofi, dan ideologi tertentu. Wallahu a’lam bish shawab
Daftar Pustaka
An-Na'im, Abdullahi Ahmed, Towards an Islamic Reform: Civil Liberties, Human Rights, and
International Law, (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1990)
Arivia, Dr. Gadis, Feminisme:
Sebuah Kata Hati, (Jakarta, Kompas, 2006)
Bone, Indriani, M.Th,
“Feminisme Kristen: Problematika Memasuki Milenium Ketiga” dalam Martin L.
Sinaga (ed.), Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga, (Jakarta: Gramedia,
2000)
Chist, Carol P. & Plaskow Judith (eds.), Womanspirit
Rising, (New york: Harper & Row, 1979)
Durkheim, Emile, The
Elementary Form of Religious Life, (New York: The Free Press, 1995)
Fakih, Mansoer, Menggeser
Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996)
Gibb, Sir Hamilton A.R.,
"Women and the Law", dalam Correspondance d'Orient, 5 (Colloque sur la Sociologie Musulmane, Actes, 11-14 September 1961)
Hafidz, Wardah, “Feminisme
sebagai Problematikan Milenium Ketiga dan Sikap Agama-Agama” dalam Martin L.
Sinaga (edit.), Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga, (Jakarta:
Gramedia, 2000)
Hassan, Riffat, "Teologi Perempuan dalam Tradisi
Islam: Sejajar di Hadapan Allah?",
Ulumul Qur'an (Jakarta, vol. 4, 1990)
Hidayat, Prof. Dr. H.M.
Komaruddin, Ketika Agama Menyejarah (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam
Filsafat Agama pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta),
(Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 24 Desember, 2001)
Majalah Rahima,
copyright@Rahima2001
Megawangi, Ratna, “Perkembangan
Teori Feminisme Masa kini dan Mendatang”, dalam Mansoer Fakih, Membincang
Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti,
2000)
Mernissi,
Fatima, Women
and Islam: A Historical and Theological Enquiry, (Oxford: Basil Blackwell, 1991)
Muslih,
Mohammad, Filsafat
Ilmu, Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, cet ke-2,
(Yogyakarta: Belukar Budaya, 2005)
Zarkasyi, Hamid Fahmi, “Tren
Pemikiran Islam di Indonesia”, dalam Jurnal Tsaqafah, vol. 2, No. 1,
Syawwal 1426 - R. Awwal 1427
[1]Makalah
disampaikan dalam rangka Workshop "Tantanga Pemikiran Islam
Kontemporer" di Gedung CIOS Institut Studi Islam Darussalam
(ISID) Pondok Modern Darusslam Gontor,
tanggal 19-20 Agustus 2006.
[2]Menurut catatan Mansoer Fakih,
setidaknya ada tiga sumber resistensi itu, yaitu, pertama, resistensi
yang berasal dari kaum perempuan sendiri yang merasa sudah puas atas peranannya
selama ini. Kedua, berasal dari proses pembangunan (developmentalisme)
yang melestarikan ketidakadilan gender, bahkan menciptakan wacana yang membuat
perempuan menjadi semakin tertindas. Ketiga, berasal dari paham
keagamaan yang patriarkis atau interpretasi atas paham keagamaan yang
dipengaruhi oleh tradisi dan budaya patriarki. Lihat Mansoer Fakih, Menggeser
Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar,1996), hal, 118-121
[3]Indriani Bone, M.Th, “Feminisme
Kristen: Problematika Memasuki Milenium Ketiga” dalam Martin L. Sinaga (ed.), Agama-Agama
Memasuki Milenium Ketiga, (Jakarta:
Gramedia, 2000), hal. 66
[4]Dr. Gadis Arivia, seorang
filsuf dan aktivis feminis dalam salah satu artikelnya menulis dengan tema:
“Pendobrakan yang Tiada Hentinya”, yang menggambarkan upaya pembongkaran (deconstruction)
tiada henti terhadap budaya patriarki. Lihat Gadis Arivia, Feminisme: Sebuah
Kata Hati, (Jakarta,
Kompas, 2006), hal. 10
[5]Sasaran utama dari proses ini
adalah untuk membangkitkan rasa emosi kaum perempuan agar bangkit untuk merubah
keadaannya, karena banyak juga di antara perempuan yang tidak sadar bahwa
mereka adalah kelompok yang ditindas oleh sistem patriarki. Lihat Ratna
Megawangi, “Perkembangan Teori Feminisme Masa kini dan Mendatang”, dalam
Mansoer Fakih, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti,
2000), hal. 225
[6]Menurut kaum feminis, budaya
patriarki ada di segala bidang kehidupan, oleh karena itu untuk
menstranformasikannya diperlukan pelbagai strategi. Maka keragaman model dan
aliran feminisme merupakan sumbangan tersendiri unttuk transformasi itu. Lihat
Carol P. Chist & Plaskow Judith (eds.), Womanspirit Rising, (New
york: Harper & Row, 1979), hal. 15
[7]Lihat Wawancara bersama Budi
Munawar Rahman dalam Majalah Rahima copyright@Rahima2001
[8]Beberapa kali pertemuan tingkat
kecamatan, di mana penulis ikut meliputnya, tema gender diangkat dan
dibicarakan, namun tidak mempertimbangkan audiensnya, padahal peserta pertemuan
adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak terlalu peduli atas isu ini.
[9]Posmodernisme yang menekankan
pluralitas, yang dengan demikian menolak universalisme, telah melahirkan upaya
dekonstruksi definisi perempuan yang dianggap sepenuhnya konstruksi laki-laki,
dan mencari akar permasalahan penindaasan perempuan berdasar lokalitas atau
konteks sosialnya. Lihat Wardah hafidz, “Feminisme sebagai Problematikan
Milenium Ketiga dan Sikap Agama-Agama” dalam Martin L. Sinaga (edit.), Agama-Agama
Memasuki Milenium Ketiga, (Jakarta:
Gramedia, 2000), hal. 94
[10]Uraian agak komprehensif
tentang Teori Krtis, lihat buku penulis, Filsafat Ilmu, Kajian atas Asumsi
Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, cet ke-2, (Yogyakarta:
Belukar Budaya, 2005), hal. 144-162
[11]Emile Durkheim, The
Elementary Form of Religious Life, (New York: The Free Press, 1995), hal.
421
[12]Prof. Dr. H.M. Komaruddin
Hidayat, Ketika Agama Menyejarah (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam
Filsafat Agama pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta), (Jakarta: IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 24 Desember, 2001), hal. 1
[13]Pada zaman jahiliyah perempuan
tidak dihormati, bahkan setiap bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Islam datang
untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini. Dan, bersama Islam kaum perempuan
dapat hidup sederajat, bahkan pda hal-hal tertentu diberi keistemawaan,
sebagaima hadits: ‘datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw seraya
bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya hormati? Beliau
bersabda: ibumu, lalu laki-laki itu bertanya, kemudian siapa? Nabi bersabda,
ibumu, dan berkata lagi, kemudian siapa lagi, beliau besabda ibumu, dan berkata
lagi, kemudian siapa? Nabi berabda, bapakmu” (HR al Bukhari dan Muslim)
(عَنْ
اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَحَقُّ
النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِى؟ قَالَ اُمُّكَ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ
ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اَبُوْكَ – رواه البخارى و
مسلم)
[14]Lihat Riffat Hassan,
"Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam: Sejajar di Hadapan
Allah?", Ulumul Qur'an (Jakarta),
4 (1990), hal. 48-55 (Pengarang ini
adalah seorang wanita Islam yang mendalami bidang sosiologi. Ia berasal dari keluarga
tradisional tetapi memperoleh pendidikan modern.)
[15]Fatima Mernissi, Women and Islam: A Historical and Theological Enquiry, (Oxford: Basil
Blackwell, 1991) (edisi
asli ditulis dalam bahasa Perancis dan diterbitkan di Paris pada tahun 1987)
[16]Mernissi, op. cit., hal. 97-99. Dua kitab yang disebutnya sebagai contoh
adalah edisi baru Kitab Ahkam an-Nisa' Ibn al Jauzi (Libanon, 1981) dan Fatawa an-Nisa' Ibn Taimiyyah. Dalam penilain Mernisi, kitab yang pertama,
dikatakan, sangat ekstrim dalam uraiannya mengenai hijab; perempuan dianjurkan untuk tidak keluar dari rumah sama
sekali dan untuk tidak lama sekali melihat laki-laki, sedang kitab yang kedua
merupakan seleksi fatwa mengenai perempuan
dari kumpulan besar fatwa-fatwa (Majmu'
al-Fatawa al-Kubra) Ibn
Taimiyyah. Menurut Mernissi, masih ada kitab yang disebutnya mengandung
pendapat jelek paling banyak mengenai perempuan, yaitu karya seorang ulama dari India, Muhammad Shiddiq
Hasan Khan al-Qannuji yang berjudul Husn
al-Uswah (edisi baru: Beirut, 1981). Dikatakan, kitab ini
juga menguraikan mengenai "ketidakmampuan perempuan berpikir
rasional dan kekurangmampuannya dalam segala urusan agama"
[17]H.A.R. Gibb, "Women and the Law", dalam Correspondance d'Orient, 5 (Colloque sur la Sociologie Musulmane,
Actes, 11-14 September 1961), Bruxelles,
hal. 233-248
[18]"...in practically every
instance the motivation of the early jurists in their elaboration of the Law in
respect to women can be resolved into
the effort to accommodate the Koranic prescription to the social pressures of their environment. Of these
pressures the most powerful was not, as has
too often been said, the influence
of Caliphs and governors, but the survival and even intensification among the tribesmen of the sense of tribal honour.
Indeed, it may even be argued that the detailed rules were dictated more in the light of traditional
conceptions of what constituted tribal 'ird than of Koranic
principles." (Gibb, op. cit., hal. 244)
[19]Seperti:
piagam PBB, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak
Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
[20]Abdullahi Ahmed An-Na'im, Towards an Islamic Reform: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, (New York: Syracuse University Press, 1990)
[21]Argumentasi Mahmud Taha tentu
lebih canggih dari pada ringkasan sederhana yang diberikan di sini.
Pemikirannya menimbulkan reaksi keras, apalagi ketika ia menentang politik
Islamisasi negara yang dimulai Numairi. Ia ditangkap sebagai oposan politik dan
kemudian dihukum mati dengan alasan riddah pada tahun 1985.
[22]Analisis kritis adalah sebuah
metode analisis yang selalu terlibat dalam upaya menemukan adanya hubungan atau
ke-saling pengaruh-an antara pemikiran; menemukan perbedaan atau melakuan
perbandingan dan akhirnya memposisikan.
[23]Menurut Hamid Fahmi Zarkasyi,
yang dimaksud dengan pandangan hidup Islam adalah pandangan hidup yang
diproyeksikan oleh wahyu dan dikembangkan oleh pemikiran para ulama otoritatif
di bidangnya masing-masing, sehingga membentuk apa yang disebut dengan conceptual
network. Lihat Hamid Fahmi Zarkasyi, “Tren Pemikiran Islam di Indonesia”,
dalam Jurnal Tsaqafah, vol. 2, No. 1, Syawwal 1426 - R. Awwal 1427, hal.
1-2
[24]Konon, setelah di Amerika
Serikat terjadi revolusi sosial dan politik, perhatian terhadap hak-hak kaum
perempuan mulai mencuat. Di tahun 1792 Mary Wollstonecraft membuat karya tulis
berjudul 'Vindication of the Right of Woman' yang isinya dapat dikatakan, meletakkan
dasar prinsip-prinsip feminisme dikemudian hari. Pada tahun-tahun 1830-1840
sejalan terhadap pemberantasan praktek perbudakan, hak-hak kaum prempuan mulai
diperhatikan, jam kerja dan gaji kaum ini mulai diperbaiki dan mereka diberi
kesempatan ikut dalam pendidikan dan diberi hak pilih, sesuatu yang selama ini
hanya dinikmati oleh kaum laki-laki. Inilah yang nantiya melahirkan feminis
liberal di Amerika.